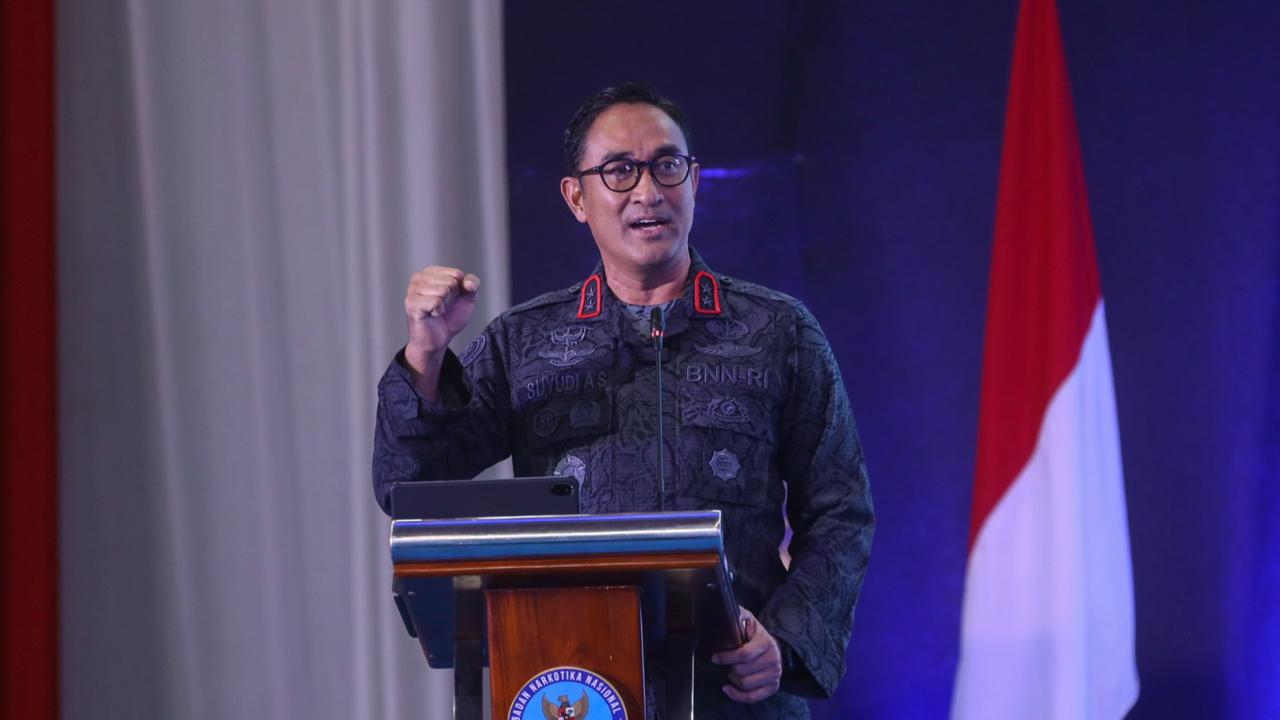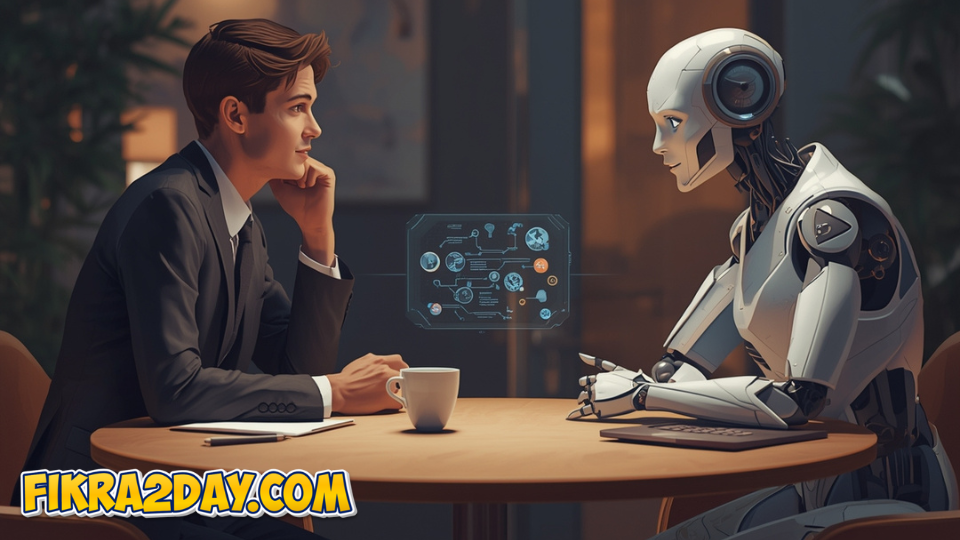TVTOGEL — Sepanjang Oktober 2025, Indonesia kembali diguncang kabar duka. Sejumlah kasus bunuh diri di kalangan pelajar mencuat di berbagai daerah — dari Jawa Barat hingga Sumatera Barat. Ironisnya, sebagian besar korban masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah pertama.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Sawahlunto, Sumatera Barat. Seorang siswa kelas VIII ditemukan tak bernyawa di ruang kelas saat jam pelajaran masih berlangsung, setelah sempat meminta izin keluar. Tak lama berselang, kasus serupa juga terjadi di sekolah asrama di wilayah yang sama.
Fenomena serupa terulang di Jawa Barat. Di Cianjur, seorang anak berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Sementara di Sukabumi, siswi madrasah tsanawiyah diduga mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengalami perundungan.
Deretan peristiwa tragis ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Ia bukan sekadar catatan kriminal, tapi menandakan adanya masalah serius pada sistem sosial dan dukungan emosional bagi remaja.
Kegagalan Kolektif Menjaga Kesehatan Mental Anak
Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, menilai meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan pelajar mencerminkan kegagalan kolektif berbagai pihak dalam menyediakan lingkungan yang aman secara emosional bagi anak dan remaja.
“Ini bukan tragedi individu, tapi refleksi dari lemahnya sistem sosial dan dukungan lintas sektor — mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak,” ujar Lisda (4/11/2025).
Lisda menjelaskan, masa remaja merupakan fase transisi kompleks, di mana perubahan biologis, psikologis, dan sosial terjadi bersamaan. Otak bagian depan yang berfungsi mengontrol impuls belum matang sepenuhnya, sedangkan sistem emosi berkembang pesat.
Kondisi itu membuat remaja lebih rentan terhadap tekanan sosial, ekspektasi akademik, maupun pencarian identitas diri. “Sering kali, mereka memendam emosi karena tidak punya ruang aman untuk gagal, sedih, atau berbeda,” jelasnya.
Remaja Rentan, Bukan Lemah
Menurut Lisda, banyak remaja sebenarnya sudah mencoba mengekspresikan kesulitan mereka — namun tidak selalu dipahami oleh orang dewasa. Tanda-tandanya sering terlihat dari perubahan perilaku, seperti menjadi pendiam, menarik diri, atau menulis hal-hal bernada sedih di media sosial.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan, kelompok usia 15–24 tahun mencatat tingkat depresi tertinggi di Tanah Air. Dari kelompok tersebut, 61 persen mengaku pernah berpikir untuk mengakhiri hidup.
Laporan WHO bahkan mencatat bahwa hampir 4 persen remaja Indonesia pernah mencoba bunuh diri dalam 12 bulan terakhir ketika survei dilakukan.
Fakta Mengerikan: Tren Bunuh Diri Anak Terus Meningkat
Data Pusiknas Polri mencatat, sepanjang 2024 terdapat 1.105 kasus bunuh diri di Indonesia. Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2023 (1.288 kasus), tren ini masih menunjukkan peningkatan jangka panjang dibanding 2020–2022.
Khusus untuk kelompok usia anak, KPAI mencatat 25 kasus bunuh diri sepanjang 2025, setelah tahun sebelumnya mencapai 43 kasus. Angka ini menandakan situasi darurat yang tak bisa lagi diabaikan.
Perspektif Psikolog: Distress Sosial dan Hilangnya Rasa Aman
Peneliti psikologi sosial dari Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menilai fenomena ini mencerminkan distress sosial dan kerapuhan sistem dukungan remaja.
Menurutnya, masa remaja adalah fase di mana sensitivitas sosial dan kebutuhan diterima sangat tinggi. Namun, kemampuan mengelola emosi dan berpikir rasional belum matang sepenuhnya.
“Ketika rasa memiliki dan dukungan sosial runtuh, rasa sakit psikologis bisa terasa absolut. Sayangnya, banyak remaja tidak punya saluran adaptif karena ekosistem sosial kini lebih menekan daripada mendukung,” jelas Wawan.
Ia menambahkan, perubahan budaya digital, tekanan akademik, dan kurangnya kehadiran emosional orang tua memperburuk kondisi tersebut. “Anak-anak kini punya banyak ruang untuk berekspresi, tapi sedikit yang benar-benar memahami mereka.”
Perlu Sistem Deteksi Dini dan Dukungan Nyata
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan pentingnya sistem deteksi dini di sekolah dan keluarga. Setiap perubahan perilaku anak harus menjadi sinyal untuk memberikan perhatian dan pendampingan psikologis segera.
“Intervensi cepat dan empatik adalah kunci pencegahan. Kita butuh psikolog sekolah, tenaga kesehatan mental di puskesmas, serta dukungan keluarga yang aktif berkomunikasi,” ujar Aris.
Ia menegaskan bahwa keluarga adalah benteng utama dalam menjaga kesehatan mental anak. Orang tua diminta tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada keseimbangan emosi dan interaksi positif di rumah.
“Pencegahan bunuh diri bukan hanya tugas psikolog, tapi tanggung jawab sosial bersama. Satu percakapan penuh empati bisa menyelamatkan nyawa,” tutup Aris.